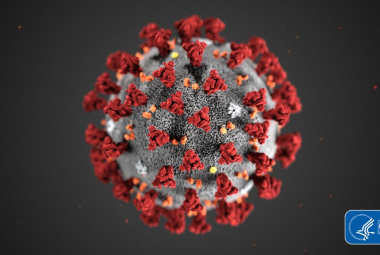"Bung, sudah sampai mana?"
"Sudah pada tahap melupakan. Aku cukup dengan gagal meyakinkannya. Tidak mau lagi membawaku terus sakit," ujarku pada Wahyu yang tengah asik pada pancingannya.
"Di tempat ini ? Kau sudah bisa lupa secepat itu?" terlihat ia kurang yakin dengan jawabanku. Aku pun memandang seberang DAM Labuhan Lama.
Sepertinya memang masih banyak kenangan yang sebaiknya kuperjuangkan. Tapi aku sudah sampai pada keyakinanku bahwa kau tak akan pernah lagi kembali.
"Bung. Perjuangkanlah apa yang sudah kau cita-citakan. Sekarang kau hanya perlu menemuinya. Meminta maaf atas keegoisanmu. Kau cukup yakinkan sekali lagi bahwa dia adalah orang yang tepat dalam hidupmu," Wahyu terus mendesakku untuk goyah.
Sebenarnya aku memang sedang bimbang. Terlebih modal maaf hari ini, rasaku sudah tidak lagi laku melihat semuanya harus dibuktikan dengan hal yang nyata. Realistis.
Aku jelas bukan siapa-siap di hadapan perempuan tangguh sepertinya.
"Bung.."
"Sudah. Lupakan."
***
Sampai sore
masih sangat lama
aku tengah menikmati kerinduan pada seseorang yang sudah tenggelam di sudut dermaga.
Semua tidak ada yang kuabadikan di sini
hanya sebatas cerita panjang yang mulai usang kugantung di atap kamar
ketika kalanya tak sanggup lagi kukenang
maka kuimpikan dia dalam pejamku....
***
Jam menunjukkan pukul 17.30 WIB. Senja mulai meruam. Kulihat sekelilingku masih saja asyik dengan pancingnya.
Aku terus seksama memperhatikan Maya dalam diam. Tak ada satupun yang ucap selain tatap kosong mengarah seberang pelabuhan lama ini. Mata sayumu tahu betul bagaimana perasaanku menyikapinya. Seperti sebongkah harap, entah harapan kosong terhadapku.
“May?” tanyaku lirih.
Maya masih saja jauh menatap. Sekali lagi aku mencoba menegurnya dengan lembut. Kuusap pundak dan kuelus manja kepalanya.
Spontan Maya menoleh. Tatapan itu memang membuatku sakit. Aku tak kuasa memandangnya dengan bola mata seperti itu. Dengan alisnya saja sudah menghanyutkanku kepada dilema, dan sekarang, dengan bola mata yang hampir menerkam semua soreku di tepian dermaga kecil ini.
“May. Apa yang Maya pikirkan?” pertanyaanku mengulang dan mencoba mengajaknya bicara. Maya hanya tersenyum.
“Maya sudah siap dengan semua pertanyaanku?” kata-kataku mulai mendalami perasaannya.
“Iya. Tapi aku minta satu syarat,” senyumnya meluruhkan siapa saja yang melihat.
Aku mulai tak kuat menahan wajah polos Maya dan mulai kualihkan pandangan darinya.
Maya menghela napas panjang.
“Apa itu?” tanyaku masih dengan keyakinan sepenuh hati.
“Bawa aku pergi dari sini, Sam,” harapnya.
“Maksudmu? Kau mau kemana?” aku mulai menyerngitkan dahi lantaran tidak begitu yakin dengan jawabannya.
“Aku sudah bosan di sini. Aku ingin kau membawaku pergi dari rumah,” ungkapnya mulai tersedu. Diceritakanlah semua latar belakang kehidupannya sampai pada titik jenuh yang membawanya jauh ke hadapanku.
Cerita kami memang sama. Aku baru saja mengenalnya. Maya memang tidak terlalu banyak bicara dibanding semua teman yang kutemui di lapangan. Maklum, setiap wartawan yang kutemui, semuanya fasih mengelola pembicaraan baik terhadap sesama maupun kepada semua orang-orang baru yang ditemui.
Pertemuan kami tidak sengaja. Niat mengenal pribadinya lebih dalam pun hanya wacana yang masih kupendam. Tidak begitu serius. Namun latarbelakang keadaanlah yang akhirnya membuatku mempertimbangkan, bahwa Maya adalah orang yang tepat menemaniku nanti.
Aku mulai bertekad mengakhiri kedilemaan ini. Kuputuskanlah untuk melamarnya.
“Baik. Kapan waktu darimu. Biar aku persiapkan dari sekarang,” kata-kataku mulai meyakinkan.
“Kapan kau siap menemui Ayahku,” katanya menantang.
“Bulan depan?”
“Baik.”
Seiring jatuhnya mentari ke dasar laut, aku meraih tangannya dan kuselipkan cincin yang tak begitu menarik. Baginya. Mungkin.
***
"Apa kau sudah paham?" tanyaku pada Ilham.
"Lalu bagaimana? Apa dengan seperti itu kau sudah meyakinkannya?" tegas Sam.
"Tidak semudah itu. Aku mencari keberadaan orangtuanya yang sama sekali belum kukenal. Tapi atas keyakinan dan niat lurusku, aku menemukan rumahnya.,"
Kuceritakanlah awal aku meminta izin kepada orangtua Maya. Dari aku kehujanan mencari rumahnya, sampai aku tergagap memohon diri untuk lebih mengenal Maya. Aku sendiri. Ya, aku sendiri menghadap dan memohnn diri untuk meminang putri semata-wayang dari keluarga sederhana. Sama sepertiku.
"Lalu, apa kau katakan niatmu melamarnya?"
"Maksudmu?
"Ya, apa kau benar-benar lurus berniat diri untuk menikahinya. Atau hanya sebatas menghilangkan statusmu saja?" ucapan Ilham membuyarkanku.
Camar-camar mengintari daun cemara. Semerbak ombak laut kian menusuk hidung kami. Aku masih belum habis pikir terhadap apa yang Ilham katakan. Sampai pada akhirnya aku memandangi jauh lautan Berkas.
Pantai ini sebelumnya membawaku pada jauh kenangan yang tak mau kuingat. Masa-masa di mana aku masih nakal dengan kisah asmaraku. Masa di mana aku sedang giatnya mencari jati diri. Sampai akhirnya harus menjerumuskan diri kepada pergaulan bebas. Dan hilang atas kepercayaan diriku melangkah maju.
"Ya atau tidak?"
"Ya. Aku kalah. Tapi, apa salah jika aku mau benar-benar memperbaiki diri,"
"Bukan harus dengan mengorbankan orang lain bukan?"
"Kenapa? Siapa yang mengorbankan orang lain?,"
Ilham lantas mengajakku menepi, menuju DAM Tapak Paderi.
Aku menunjukkan satu tempat kesukaan kami.
Hampir setiap sore kami kesini. Pantai Malabero, seberang sebelum menuju DAM Tapak Paderi.
Ilham hanya tersenyum. Ia tau betul bahwa aku masih benar-benar menyayangi Maya.
"Lalu bagaimana jika setelah itu, Maya tau semua tentangmu? Bukankah kau sudah dewasa? Segala pertimbangan jangan hanya jatuh pada satu pihak, Sam,"
"Ah, kau sama saja dengan Wahyu. Sama sekali tidak membantu,"
"Bukan demikian. Lalu, bagaimana jika kekecewaan nantinya menghantam perasaan Maya. Kau tidak kasihan dengannya? Dia sudah cukup menderita meski itu melatih daya tahan hatinya hidup di masyarakat. Kau kira saja jika hal demikian terjadi di pihakmu," nasehat Ilham ada benarnya.
"Lalu, aku harus bagaimana?"
"Kau buang jauh-jauh niatmu dulu. Benarkan. Luruskan semuanya. Baru kita bicara lagi," kata Ilham.
Sampai di ujung DAM, kami hanya terdiam melihat senja yang terus menggalau. Sama seperti yang kurasa. Dan atas apa yang Ilham katakan, aku mulai memikirkannya.
***
Seiring nada sumbang yang keluar dari mulutmu, aku menyambut petang dengan sedikit hati-hati. Tapi setelah kuputuskan untuk tidak lagi mempertimbangkan waktu, walau pahit, tetap kuhempas jua.
Doa sepertiga malam yang selalu kuucap mendekati masanya, begitu deras kuhaturkan pada yang maha kasih. Aku tau, meski keputusan ada di tangan Tuhan, tapi setengahnya keputusan itu milikmu. Aku hanya bisa berharap dan terus berdoa sampai bertemu pada titik jemu dan menunggu.
Aku memang begitu lemah, menimbang aku bukan siapa-siapa, juga tak memiliki apa-apa. Tapi, rasaku jauh lebih lemah bila hati sudah disandingkan dengan ketidaksejalanan perasaan dan harapan. Memang, semestinya aku tak harus menghempaskan seluruhnya rasa itu.
Sore semakin sunyi. Kucoba merenungi tentang jalan hidupku dipertemukanmu.
Seperti Gelato yang sering kunikmati di Rumah Makan Pesisir, rasanya. Nikmat hanya sebatas lidah, dan setelahnya tetap hambar dipandang malam.
"Bung!", Seno datang mengagetkanku.
"Eh, kau, Sen. Dari mana?" aku menimpalinya dengan sedikit kesal.
"Kenapa melamun. Kau masih cinta?" Seno tahu betul maksud dan tujuanku mampir di kedainya. Menggalau.
"Entahlah. Sama halnya dengan niatku pertama kali. Memaksakan cinta. Dan harusnya aku memaksakan lupa," senyumku sembari menutup cahaya senja di Labuhan Lama Malabero. (Bersambung)
**
Bengkulu, 15 Desember 2019
M Bisri, Komunitas Menulis Bengkulu