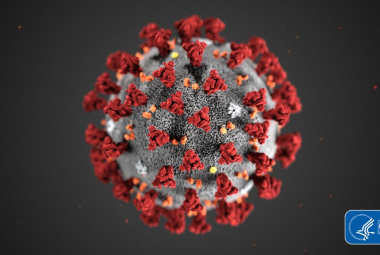Ketika kesenduan ini enggan pergi, aku segera menepi, mengunjungi Labuhan Lama Malabero dan menampikkan diri di ujung Sungai Pondok Kelapa demi mengadu asa pada senja yang menerka.
Sore itu tak satupun orang kutemui mengadu sesegukan seperti biasanya. Hanya camar-camar dan deburan ombak memecah kesunyian hatiku. Di sini, aku menatap tajam pada senja itu. Segera terbayang rona wajahmu seiring merah jingga yang menyapu diksi semesta hingga melarut-redamkan amarah.
Hampir sebulan terakhir aku tak pernah lepas dari pesakitan yang terus mendera. Dengan luka menganga, kau tinggalkan rasaku di ambang kasih sayang yang terus bertanya,”mengapa kita dipertemukan bila akhirnya rasa berterus-terang dengan ketiadaan?".
Orang menyebutku Fatimah. Umur yang sudah mulai matang ini betapapun tidak ingin segera menimang putra dari lelaki tampan yang pernah kutemui di pesisir Sungai Pondok Kelapa ini. Aku lupa berapa lama waktu yang kulewati hingga akhirnya tak sekalipun bertemu lagi dengan pria bersepeda onthel itu.
Pernah sekali, aku mendengar, menguping pembicaraan tetangga yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang selalu lewat di depan bilik dengan sepedanya. Setibanya di halaman rumah, ia selalu menguntit jendela kamarku. Namun tak sekalipun aku tau siapa dia dan apa maksud tujuannya mengintip rumah orang.
Beberapa hari terakhir, ayah juga menceritakan betapa orang ini sangat serius ingin menemuiku. Tapi aku tak peduli sekalipun dengannya. Aku hanya tetap berharap agar dapat menemui lelaki yang senantiasa berdiri di tepi Sungai Lemau. Melihat senja dengan sepeda onthelnya yang tak pernah ditinggal kemanapun ia pergi.
“Bukan. Bukan sekali aku bertemu dengannya. Iya. Aku pernah bertemu dengan pria bertopi jerami di Pasar Ikan. Bukan cuma di pantai,’’ kata-kataku menerka mengembalikan ingatan.
Tapi sayang aku tak pernah tahu namanya.
***
Negeri kaya-raya ini sepertinya penuh kenangan. Hilir mudik etnis Tionghoa mengajarkan juga betapa beragamnya bumi pertiwi. Beberapa dekade terakhir, aku melihat perubahan begitu cepat mengubah Pasar Benculen menjadi pusat perdagangan bangsa-bangsa asing. Kapal-kapal kecil juga banyak kutemui di Pelabuhan Boom Tapak Paderi. Sesekali, sepulang dari pasar, aku sengajakan diri melihat banyaknya penyu hijau mampir di pesisir pantai tanpa ada satupun yang mengganggunya.
Jarak rumah ke pasar cukup jauh. Hampir 7 kilo meter. Baiu, kerbau gerobak yang setia mengantarku berbelanja bahan-bahan untuk dibuat kerajinan.
Setelahnya, aku mampir ke surau di mana tempat orang tua mengajarkan anak-anaknya mengaji. Tempat di mana ayahku, Hafiz, mendidik generasi emas bangsa ini, menjadi garda terdepan Benculen sebagaimana harapan ayah untuk menjadi pusat pendidikan terbesar di Pulau Sumatra.
Sore ini aku menemuinya di surau. Belum sampai ke ruangan kecil yang disebut bilik, segerombolan anak-anak menggodaku.
“Tima... Ade Tun Mesoako. Gacang ba masuk,” serunya dengan nada terburu-buru sembari menarik selendang besurek.
“Siapa?’’ tanyaku biasa.
“Ada, lah. Cepatlah sedikit, Tima,” ujar Samsu, murid kesayangan ayah.
Aku berjalan tergopoh-gopoh, penasaran dengan apa yang budak-budak sampaikan.
“Assalamualaikum, Ayah.” Kusambut tangan ayah yang sedang memegang lidi sebagai telunjuk muridnya mengaji.
“Waalaikumsalam. Kau Tima. Sini, duduk samping ayah.”
“Tadi, ada yang mencarimu.” kata lelaki dengan celana cingkrang itu.
“Siapa kah gerangan, Yah?” tanyaku makin keheranan.
“Koesno. Murid yang pernah ayah ceritakan kepadamu. Ia Ingin bertemu denganmu. Bukankah kau sudah kenal?”
“Koesno?” Aku tidak mengenal nama laki-laki mana pun. Ayah juga tahu, usia remajaku hanya kuhabiskan dengan menjahit kain-kain besurek bercorak kaganga. Juga membantu Ibu membuat berbagai kerajinan dari rotan. Jadi, mana mungkin dia bertanya seperti itu. Aku tau, ayah hanya menggodaku.
“Iya. Dia sering melihatmu di Pantai Paderi. Apa gerangan kau senang sekali menepi di pesisir Paderi?’’
“Ah, tidak ayah. Manalah pernah aku ke pantai itu. Hanya sesekali. Aku juga tak mengenal laki-laki manapun selaian ayah.” seruku manja. Sesekali, ya hanya sesekali aku ke Tapak Paderi dan tak ada satupun kutemui. Berbeda dengan pria yang pernah kulihat di Sungai Pondok Kelapa.
“Ah. Anakku. Baiklah. Katanya, besok ia akan mampir kerumah,” apa yang Ayah sampaikan membuatku kian penasaran.
Ayah lantas mengusap kepalaku, kemudian mempersilahkanku pergi pulang. Ia meneruskan kajiannya bersama anak-anak yang sedari tadi menungguku pergi, aku mohon diri untuk pulang terlebih dulu ke rumah.
“Koesno, siapa laki-laki itu. Sampai dia sok tahu aku sering singgah ke Paderi.
***
Perempuan lugu sepertiku tidaklah mengenal cinta. Sekalipun dari pria yang begitu dihormati, ayah, tak pernah terlihat berlebihan mencintaiku. Aku memakluminya sebagaimana orang menghormatinya penuh. Wajar. Ayah adalah tetua yang begitu dihormati di Pondok Kelapa ini.
Negeri Bangkahulu sekali lagi memancarkan pendar kerinduan. Sepoi-sepoi angin laut menyibak kerudungku. Kuputuskan untuk kembali menghampiri Sungai Pondok Kelapa itu.
***
“Ini pria yang menemui ayah kemarin,” kata Ayahku.
“Hai, Fatimah. Aku Sukarno. Namun orang lebih senang menyebutku sebagai Koesno. Panggil saja namaku Karno.”
Basa-basi. Aku hanya menyingkap senyumku jauh ke luar jendela. Tak sengaja, aku melihat sepeda onthel yang pernah kutemui di Sungai Lemau saat ini terpampang di halaman rumahku. Lamunanku kembali mengingat apa yang tetangga kami sampaikan bahwa dikau benar-benar Koesno yang kutemui di sungai itu.
“Apa kau sudah lama mengenalnya, Tima?” kata Hafiz, Ayahku.
Sejurus aku tersipu. Jadi ini laki-laki yang sering kutemui di Sungai Pondok Kelapa. Apa gerangan singgah ke rumahku.
Koesno mohon diri mengungkap maksud dan tujuannya, “Aku sudah lama memperhatikanmu, Fat. Dan mohon maaf jika aku lancang. Kemudian dari pada itu, kau juga belum begitu mengenal siapa Aku, Ayahanda Hafiz. Atas itu semua aku harap kau tidak tersinggung apabila maksudku adalah untuk mendekatkan diri bersilaturahmi. Aku mohon diri mengenal lebih jauh siapa Fat. Izinkan aku menjadi murid Ayahanda Hafiz dan mohon diri meminang Tima,” kata Karno dengan tekad.
Wajah merah merundungi Fat. Sejurus ia menatap ayahnya. Wajah dingin Hafiz membuat Fat salah tingkah.
“Aku sudah tau siapa kau, Koesno. Kuacungi jempol atas keberanianmu menyampaikan etikad baik kepada keluarga kami. Namun itu semua tak serta merta kuiyakan. Keputusan harus kami ambil berdua. Namun secara sepihak, aku merestuimu. Tinggal kembali kehati Fat. Apakah ia mau menerimamu tanpa perkenalan terlebih dahulu,” sampai Hafiz.
Koesno tau maksud perkataannya. Dipalingkannya ke wajah Tima, dan ada tanda iya di sana.
***
Koesno mengagumi setiap bentuk keindahan. Ia menarik nafas dalam-dalam setiap menatap hamparan pemandangan negerinya yang molek. Negeri Bangkahulu. Bersandar manja akan dahan kelapa, melambai-lambaikan tangannya ke arah dua sejoli di Tepian Sungai Pondok Kelapa.
Koesno mengagungkan asma Allah setiap melihat wanita cantik ciptaanNya. Begitupun ketika Koesno menatap wajah ayu Fatimah.
Koesno tak menampik. Terhadap wanita-wanita yang mengisi hatinya, semua mendapat tempat yang begitu mulia di hati Koesno. Inggit Garnasih sebagai perempuan gigih, penyayang, dan mendukungnya sejak era pergerakan hingga menjelang Indonesia merdeka. Fatimah? Ia gadis 19 tahun yang ceria. Sudah sebulan hubungan ini berjalan. Mungkinkah akan dinikahinya?
Fatimah pun ditaburi cinta Koesno. Tak sekalipun Ia tau bahwa akan dijadikan yang kedua setelah Inggit. Ia selalu menceritakan kisah betapa eloknya negeri ini. Adapun Fatimah, sebagai penopang semangat Koesno di negeri buangan. Semua diutarakan Koesno dalam waktu yang tak singkat. Berjalan satu bulan, Koesno mengutarakan niat menikahi Fatimah.
Namun, Fatimah tak begitu paham seluk beluk lelaki pujaannya saat ini. Yang ia tau, Koesno begitu terampil merangkai kata. Sampai tak selidah katapun melesat salah sasaran ketika diucapkannya.
Siapa sangka, kala itu, Koesno justru masih bersama perempuannya, Inggit. Dan Fatimah, akankah kembali mengisi keduakali hati sang pujangga.
***
“Kau menyangka bahwa aku telah menaruh rasa kepada wanita lain yang baru saja kukenal. Padahal, justru sebaliknya, bukan. Aku sudah lama mengagumimu. Sudah hampir sebulan, aku melihatmu setiap minggu datang ke tempat di mana hanya kita berdua yang bisa membaca dan memahami hangatnya senja di Sungai Pondok Kelapa. Jauh dari hiruk-pikuk Kota Tuo yang selalu meninggalkan keluh-kesah di rantau, kota kelam dengan sentuhan ambigu dan samar,” Koesno mangut, mengutarakan maksud dan tujuannya.
“Aku mengira kita akan tetap bersama menjalani senja-senja diafan hingga waktu benar-benar mempersatukan hubungan ini. Dengan ikatan sah tentunya,’’ wajah pucat sayu mengurung Fatimah sore itu.
Koesno paham betul hati Fatimah sudah termakan rayuannya. Namun, ada yang lebih genting ketika Koesno harus kembali ke Jakarta. Teman-temannya akan menjemputnya dari pengasingannya di Negeri Bangkahulu. Koesno harus benar-benar meyakinkan bahwa sekembalinya nanti, ada dua kunci yang ia bawa ke hadapan Tima. Satu, menikahinya, dan kedua membawa negeri ini merdeka.
“Apakah kau ingat, ketika pertamakali aku mengenalkanmu pada keindahan senja di Sungai Lemau ini. Saat di mana waktu itu kau tengah merintih kesakitan karna dikhianati negerimu sendiri, dan aku datang dengan latarbelakang yang sama, mengenalkan arti kesepian yang amat damai,” kalimat Tima menjatuhkan niat Koesno.
Koesno ingat betul betapa saat tragedi perang dunia ke II pecah, Ia harus dibuang jauh dari negerinya. Oleh teman-temannya, yang saat itu tidak paham akan kekuasaanya menahan rindu kemerdekaan. Tapi Koesno bertahan. Dia kuatkan istiqamahnya. Dan terus berdoa keribaan Tuhan atas pilihannya yang sangat mendesak. Mundur selangkah, atau ia harus mati lebih cepat.
“Fatimah. Senja itu, walau berkarat-karat, ia tetap tegar menepiskan rasa gundah. Rindu yang hampir tak pernah letih menyingahi, hingga akhirnya pupus tenggelam bersama merah jingga yang kusebut Rona Teras Senja. Dan setibanya kau di sini bersamaku, sejauh ini, senja itu kian teduh menjadi teras peraduan. Hampir tak ada drama, tak ada kebohongan, tak ada pula kontemplasi. Dan akhir cerita kau menghapuskan keraguanku menatapmu,” kata Koesno kemudian mengusap kepala Tima.
“Aku akan kembali. Percayalah,” kata Koesno.
“Baiklah, jika memang demikian akhirnya. Aku mengalah dan tak akan kembali lagi mengungkit masalahmu. Tentangmu, juga tentangku,” Tima masih tak paham.
Koesno terdiam. Ia melangkah menghadap ke sepeda onthelnya, “Banyak yang kululaui bersamamu, Fatimah. Dan tak akan mungkin aku meninggalkanmu dalam keadaan tak semerdeka negeriku nanti,” ungkapnya dalam hati.
***
Matahari mulai benar-benar tenggelam. Tak seperti kemarin, Koesno Dilema.
“Kudengar sayup-sayup namamu juga terdampar di sisinya. Ah, andai saja senja ini tak seindah cerita kita kemarin, pasti sudah kusempatkan menggenggamnya, kukantongi di dalam saku dan kubawa pulang ke rumah untuk kukenalkan suatu saat kepada anak-anakku,” terdengar seperti sajak, Koesno menggenggam tangan Fatmawati.
Wajah Fatmawati, seperti bunga pucuk ranumnya menggeliat menyisakan kenang di Pantai Tapak Paderi.
Tidak ada esok hari di sini, tidak ada juga sapa yang akan kembali kugali. Kuhempaskan seluruh ketiadaan ini agar aku lekas lupa dengan semua yang kusebut dilema. Koesno ingkar janji. Ia terus memuji dan meyakinkan hati Fatmawati. Fatimah, perempuan manis dengan lesung pipitnya yang menggoda, harus rela jadi korban penghianatan Koesno.
“Esok aku akan segera pergi meninggalkan Kota Tuo yang lugu. Jelas kuindahkan segala cita-cita dan cinta yang pernah terbenam di dalamnya. Kota Tuo yang ketika kusapa menjadi ibu dan rumahku, dan guru beserta ladang ilmu yang tak akan pernah mati kubawa. Entah di tempat baruku nanti, atau mungkin juga ketika aku mendidik anak-anakku dengan kesenduan Kota penuh luka. Kau janji akan menungguku Fat?” kata Koesno.
Antara Fatimah dan Fatmawati, Koesno kembali membuat hati perempuan terluka. Belum selesai Inggit, kini ia harus meluluhlantakkan hati Fatimah. Rupanya, perkenalan antara Fatimah dan Fatmawati pada waktu yang sama. Dan siapa yang harus dipilih, dialah perempuan yang akan menemani Koesno dari jatuh bangunnya negeri ini.
“Fat, kutitipkan seribu ceritera senja kepadamu. Jangan kau ceritakan di mana letak kebahagiaanku bersamamu. Karna dalam bentuk puing kerinduan ini, aku tak akan mungkin kembali menyadurnya menjadi bulatan angka genap di jari kita. Aku akan membawamu ke gerbang kemerdekaan negeriku, Fat”.
***
Setelah hari itu, Koesno tak lagi mendatangi Siti Fatimah. Ada yang dilupakan dari sekian banyak daftar untuk memerdekakan bangsanya. Mengambil salah satu putri terbaik Negeri Bangkahulu, Koesno justru lupa akan sajak-sajak serenada yang telah banyak meluluhkan hati perempuan di Negeri buangannya.
Dan Fatmawati, ia adalah perempuan terbaik sebagai wakil bangsa ini merdeka.
* Bisri Mustofa, Cerpenis